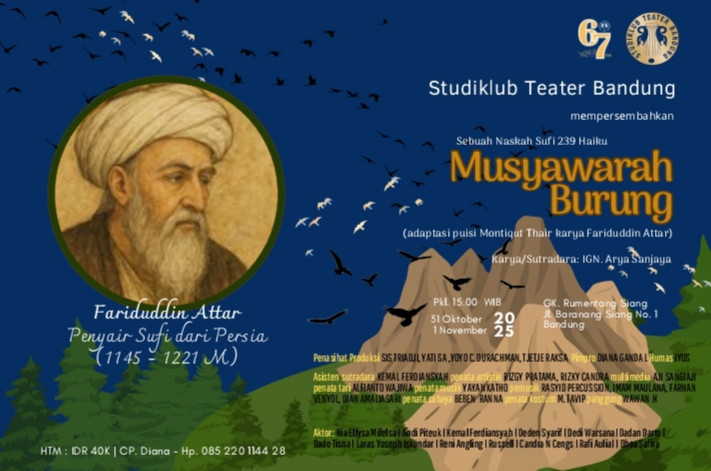INDRAMAYU, TINTAHIJAU.com — Di tanah pesisir yang kerap disapa angin asin dan cahaya senja, wayang cepak dan tari topeng pernah tumbuh laksana denyut nadi kehidupan. Di Indramayu, Cirebon, dan wilayah sekitarnya, kesenian itu dulu berjejal di tiap sudut kampung—hidup, riuh, dan akrab dengan rakyat. Kini, ia seperti nyala lampu minyak di tengah badai zaman: masih menyala, meski redup dan sendirian.
Di Desa Gadingan, Kecamatan Sliyeg, berdiri sebuah sanggar yang menolak tunduk pada lupa. Sanggar Jaka Baru namanya. Selasa, 13 Januari 2026, waktu seakan melambat di sana. Bangunannya sederhana namun terawat, menyimpan ratusan wayang cepak dan topeng—benda-benda kayu yang bukan sekadar kerajinan, melainkan penanda ingatan dan doa yang dipahat tangan-tangan setia.
Di sanalah Ki Warsad Darya, 87 tahun, menua bersama bayang-bayang tokoh pewayangan. Ia adalah pendiri Sanggar Jaka Baru, dalang yang telah menapaki puluhan ribu malam pertunjukan. Suaranya pelan, namun kisahnya panjang—mengalir seperti sungai yang pernah meluap, kini berusaha tetap mengalir meski arusnya melemah.
Sanggar ini lahir pada 1964, di masa negeri diliputi kecemasan. Riak politik kala itu membuat masyarakat resah, meski Ki Warsad menegaskan, berdirinya Jaka Baru bukan soal ideologi, melainkan luka batin. Ia memulai karier mendalang dengan menyewa wayang milik kerabat sejak 1962. Namun, tanpa sebab yang jelas, penyewaan itu dihentikan. Dari rasa sakit hati itulah tekadnya tumbuh: membuat wayang sendiri, mendirikan sanggar sendiri, dan menamai perjuangannya Jaka Baru—cerminan dirinya yang kala itu masih perjaka.
“Sebelum ada Jaka Baru, saya pentas tanpa nama,” kenangnya lirih, seolah sedang membuka lembaran lama yang telah menguning.
Masa kejayaan datang bagai musim panen. Antara 1964 hingga 1970, Sanggar Jaka Baru bisa mementas hingga 150 kali setahun. Seratus kali pentas pun dianggap biasa. Ki Warsad bahkan kerap lupa pulang. Pernah ia langsung berangkat dari Bogor Sukra menuju Lombang Juntinyuat, tanpa singgah sejenak untuk merebahkan tubuh.
Hampir seluruh Indramayu telah disambanginya. Sepeda dan pedati menjadi saksi perjalanan seni itu—gong besar diangkut di atas oplet, para pemain berdesakan, sebagian lainnya mengayuh sepeda menyusul rombongan. Bayaran kala itu bukan uang, melainkan padi: lima kuintal untuk desa sendiri dan tetangga, tujuh kuintal untuk wilayah yang lebih jauh. Sebuah transaksi yang terasa lebih jujur, lebih membumi.
Zaman kemudian berganti wajah. Uang tunai menggantikan padi, dengan nilai Rp10 juta hingga Rp15 juta per pentas. Panggung pun meluas: dari kampung-kampung Indramayu dan Cirebon, menuju Brebes, Tegal, Subang, Gedung Sate di Bandung, kampus-kampus, Yogyakarta, hingga akhirnya menyeberang samudra. Tahun 1994, wayang cepak menjejak Hiroshima, Jepang, dalam Asian Games. Sebuah kebanggaan yang membuat mata Ki Warsad berkaca-kaca—seni desa diakui dunia.
Namun, roda waktu tak pernah berjanji setia. Sejak 2018, Ki Warsad berhenti mendalang. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Ia menyerahkan kelir kepada anak-anaknya. Dengan nada getir, ia mengakui perubahan zaman telah menggeser selera. Wayang cepak kini hanya dinikmati segelintir orang. Dalam setahun, pementasan paling banyak belasan kali—sekadar menyambung hidup.
Meski begitu, Sanggar Jaka Baru belum menyerah. Wayang cepak, topeng Indramayu-Cirebon, dan berokan terus dibuat dan dijual. Dua paket wayang bahkan dijadwalkan terbang ke Amerika Serikat melalui Yogyakarta pada Januari 2026—tanda bahwa napas tradisi ini masih mampu menyeberangi batas.
Lima anak Ki Warsad menjadi lanjutan kisah ini. Putri sulungnya, seorang sintren, telah lebih dulu berpulang. Anak kedua memilih jalan lain. Dua putranya meneruskan jejak sebagai dalang, sementara putri bungsunya menyiapkan busana wayang dan menjahit pakaian untuk warga sekitar.
Sanggar Jaka Baru kini berdiri sebagai penjaga sunyi warisan. Ia mungkin tak lagi seramai dulu, namun di setiap pahatan kayu dan denting gamelan, tersimpan tekad yang tak ingin padam: bahwa selama masih ada yang mau bercerita, wayang cepak akan tetap hidup—meski pelan, meski tertatih—di tengah zaman yang terus berlari.