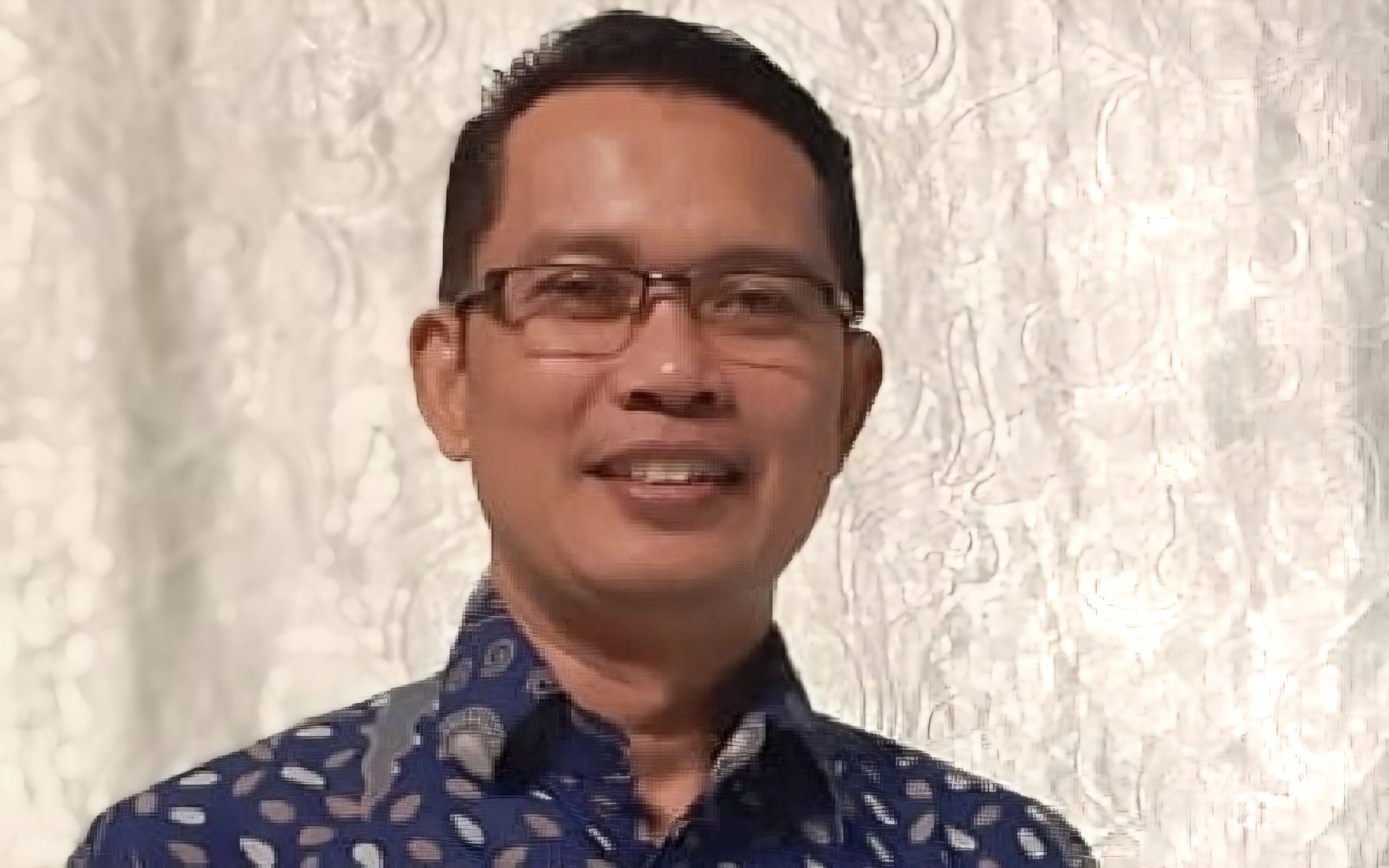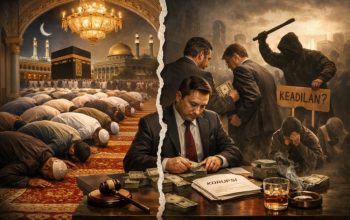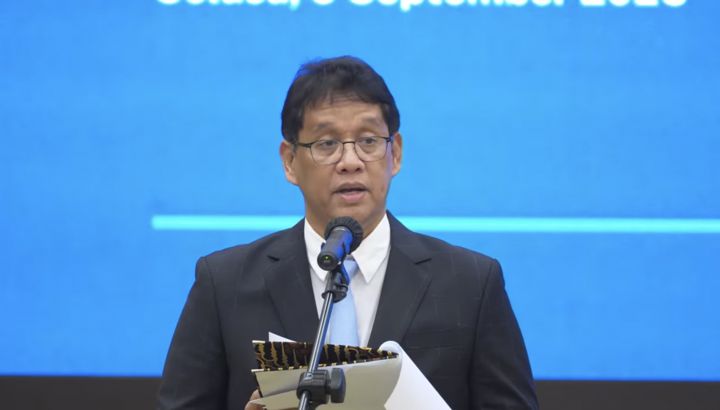WARGA Pasundan tentu tak asing dengan gaya bicara Dedi Mulyadi. Logat Subang-nya kental, gaya bahasanya sering memikat, dan narasi-narasinya selalu menyentuh akar budaya Sunda. Tapi belum lama ini, Dedi tampil berbeda.
Dalam sebuah acara resmi yang dihadirinya di Ciasem, amarahnya ditunjukkan saat sebuah spanduk bertuliskan “Save Persikas” tiba-tiba dibentangkan oleh sekelompok pemuda. Dedi sontak menegur dengan suara tinggi, bahkan melontarkan kata-kata bernada keras. Video kemarahannya pun viral.
Sebagian netizen merasa Dedi terlalu emosional. Tapi bagi saya, yang pernah menjadi adik kelasnya di SMPN 1 Kalijati, ekspresi itu bukan hal yang asing. Saya paham betul, itu bukan marah yang asal meletup. Itu jenis amarah yang dulu kerap kami temui di sekolah. Para guru kami—saat itu ada tiga guru senior di sekolah tersebut—adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Mereka tidak segan menegur keras siswa yang ngobrol saat upacara atau bertingkah tidak sopan di lapangan. Bahkan ada yang dijewer dan dibawa ke depan barisan. Saat itu kami tidak merasa dilecehkan, karena kami tahu: itu bagian dari mendidik.
Dedi Mulyadi tumbuh dari akar tradisi itu. Maka tak heran jika ia merasa wajib menegur ketika sebuah tindakan dianggap tidak sopan terhadap ruang dan waktu. Dalam kacamata psikologi sosial, marah seperti itu sering disebut sebagai moral anger—amarah karena adanya pelanggaran norma, bukan karena kepentingan pribadi. Ia marah karena merasa nilai sopan santun dilanggar. Sebuah acara formal disisipi aspirasi bola yang tidak pada tempatnya. Ia tak ingin acara menjadi ajang interupsi.
Namun tantangannya, hari ini bukan lagi tahun 1980-an. Dulu, amarah seperti itu bisa jadi sarana pendidikan sosial. Kini, di era demokrasi digital, semua bisa direkam, dipotong, dipelintir, lalu disebarluaskan ke dunia maya. Amarah yang dulu dianggap wajar, hari ini bisa dituduh sebagai bentuk arogansi. Apalagi jika dilakukan oleh tokoh publik, yang setiap kata dan gesturnya selalu ditakar dengan kaca pembesar.
Dedi mungkin saat itu lupa, bahwa audiens hari ini tidak hanya para sesepuh atau tokoh adat yang paham konteks budaya. Generasi muda yang dominan di dunia digital menilai pemimpin dari cara mereka mengelola emosi. Bukan sekadar tegas, tapi juga empatik dan terbuka terhadap kritik. Amarah yang keras, tanpa komunikasi lanjutan yang menjelaskan, bisa berbalik arah jadi bumerang politik.
Namun netizen seharusnya juga bijak dalam menilai. Kita perlu membedakan antara pemimpin yang marah karena rasa tanggung jawab, dengan pemimpin yang marah karena ego. Jika KDM marah karena ingin menjaga ketertiban forum, itu bisa dimaklumi. Tapi jika ekspresi itu melewati batas kesopanan publik, kritik tetap perlu disampaikan—dengan cara yang santun pula.
Sebagai urang Sunda, kita diajarkan prinsip “teu ngaleuwihan, teu ngurangan”. Tegas boleh, tapi tetap harus dituntun ku rasa. Wibawa seorang pemimpin tak hanya lahir dari suara lantang, tapi juga dari kemampuannya membaca zaman. Di tengah masyarakat yang makin plural, seorang pemimpin dituntut mampu menyeimbangkan nilai-nilai lama dengan cara komunikasi yang baru.
Dedi Mulyadi tetaplah tokoh yang punya tempat tersendiri di hati masyarakat Pasundan. Tapi zaman bergerak. Gaya kepemimpinan pun perlu beradaptasi. Di era digital ini, kearifan lokal bukan berarti keras kepala. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan nilai-nilai itu dengan cara yang bisa diterima semua generasi—tanpa kehilangan substansi.
Karena sejatinya, pemimpin yang bijak bukan hanya yang mampu marah saat norma dilanggar. Tapi juga yang mampu menjadikan amarahnya sebagai cermin untuk menata ruang publik yang lebih beradab. Dan, itu semua tampaknya dipahami dan disadari KDM setelah amarahnya surut.
Oleh: Budi Setiawan, Penulis adalah pemerhati sosial-politik, mantan jurnalis senior ibukota, alumnus FISIP Unpad Bandung