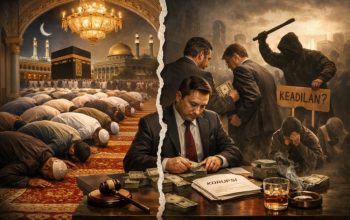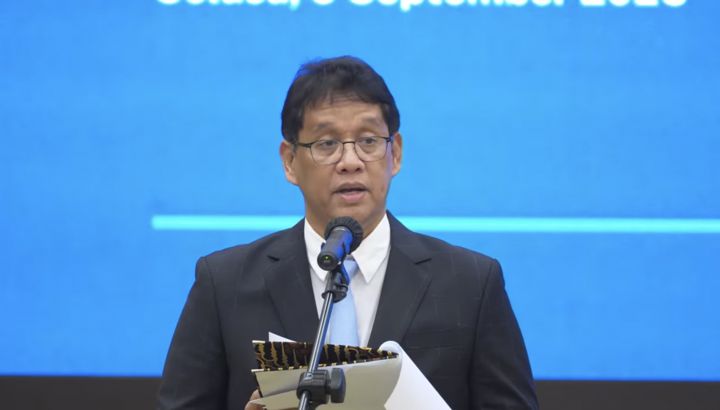Ibadah haji telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam Nusantara sejak abad ke-13, seiring dengan masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia. Perjalanan ke Tanah Suci Makkah belum hanya soal ritual ibadah; melainkan juga merupakan cermin dinamika sosial-politik, identitas, dan semangat yang dimiliki masyarakat pribumi selama masa penjajahan.
Sebagai rukun Islam kelima, haji memiliki urgensi religius yang tinggi. Namun, di era pra-kemerdekaan, perjalanan menunaikan ibadah ini menghadapi segala macam tantangan, mulai dari kondisi pelayaran yang ekstrem, intervensi kolonial, hingga mobilisasi spiritual yang membangkitkan nasionalisme (Historiografi Manajemen Haji di Indonesia, Muhammad Irfai Muslim, 2020).
- Sejarah Awal Pelaksanaan Haji oleh Umat Nusantara
Perjalanan haji umat Islam Nusantara diperkirakan telah dimulai sejak abad ke-16. Pada masa awal, jamaah berangkat ke Makkah melalui jalur laut, menggunakan kapal dagang atau tradisional, dengan perjalanan yang sangat panjang dan berbahaya. Mereka menghadapi kesulitan seperti cuaca ekstrem, keterbatasan pangan dan air, serta wabah penyakit yang kerap menyerang selama penyeberangan (Nurai, 2017 dalam Historiografi Manajemen Haji di Indonesia). Kondisi ini belum lagi dihadapkn dengan kriminalitas, penipuan, dan pemerasan terhadap jamaah yang tidak fasih berbahasa Arab ataupun memahami prosedur formal ke Makkah.
- Intervensi Kolonial Belanda: Pengawasan dan Regulasi Ketat
Seiring perkembangan kekuasaan Belanda di Nusantara sejak abad ke-17 dan seterusnya, mereka mulai mengatur perjalanan haji secara sistematis. Pemerintah kolonial menerapkan berbagai kebijakan, seperti Ordonansi Haji tahun 1825 dan 1859, yang mewajibkan calon jamaah memiliki paspor, membayar pajak tinggi, serta menjalani prosedur birokrasi melalui Kantor Urusan Pribumi agar pergerakannya dapat dipantau aktif (Ordonansi Haji 1825, Resolusi 1825, Ordinansi 1859) Selain itu, VOC bahkan mulai melakukan ‘screening’ sebelum dan sesudah haji sejak akhir abad ke-17
Motivasi Belanda dalam membatasi dan mengawasi keberangkatan haji berkaitan dengan kekhawatiran bahwa jamaah haji dapat terpapar ide-ide perlawanan di Tanah Suci dan kemudian menyebarkannya di tanah air. Maka, pembatasan ini bukan semata administratif, melainkan sarana kontrol politis (Muhammad Irfai Muslim).
- Kendala Masa Perang Jepang: Pelarangan Haji
Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), pemerintah Jepang sama sekali tidak memfasilitasi atau memberikan rute keluar untuk pelaksanaan haji. Tidak ada transportasi maupun izin resmi, sehingga keberangkatan terhenti total. Situasi perang dan prioritas militer membuat haji menjadi ibadah yang tidak dapat dijalankan umat Islam Indonesia selama periode ini . - Peran Intelektual dan Organisasi Islam dalam Perbaikan Haji
Sebelum kemerdekaan, lembaga-lembaga Islam seperti Persyarikatan Muhammadiyah mulai mengambil inisiatif untuk memperbaiki perjalanan haji. Pada tahun 1921, KH Ahmad Dahlan membentuk Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH Muhammad Syudja’. Mereka juga membentuk Komite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia. Kongres Muhammadiyah tahun 1930 merekomendasikan pengadaan pelayaran mandiri untuk mengangkut jamaah haji Indonesia — strategi penting dalam menolong umat dan mengurangi ketergantungan pada kapal kolonial Belanda.
- “Politik Haji” dan Mobilisasi Nasionalisme
Revolusi nasional dan upaya mempertahankan kemerdekaan juga tercermin lewat dinamika haji. M. Shaleh Putuhena mencatat praktik “Politik Haji” yang dilakukan oleh kolonial maupun nasionalis sendiri sejak abad ke-17 hingga abad ke-20. Di masa revolusi (1945–1949), Belanda mencoba merebut simpati masyarakat Islam dengan menawarkan fasilitas haji sebagai propaganda politik — hal ini pun ditolak keras oleh pejuang Indonesia yang memahami konteksnya (TjHeR, 2025). - Misi Haji Resmi Republik Indonesia: Diplomasi dan Pengakuan
Menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan, Indonesia mulai mengirim misi haji resmi yang membawa misi diplomatik penting:
1948: Rombongan pertama (Misi Haji I) dipimpin oleh KH Mohammad Adnan, bersama Saleh Su’ady, H. Syamsir, dan Ismail Banda. Mereka menunaikan haji sekaligus melakukan kontak dengan Raja Ibnu Saud dan pemimpin negara Islam lainnya untuk meminta pengakuan kemerdekaan RI.
1949: Rombongan resmi kedua dikirim setelah Perang Dunia II berakhir. Anggotanya antara lain H. Abd Hamid, M. Noor Ibrahimy, Prof Ali Hasjmy, Prof Abdul Kahar Mudzakkir, dan H. Sjamsir. Mereka bertugas tidak hanya melaksanakan ibadah, melainkan juga menggalang dukungan internasional di dunia Islam untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Pengakuan Kedaulatan RI akhir 1949, pengelolaan haji mulai digerakkan pemerintah.
Pada 1950, pemerintah memberangkatkan jamaah haji menggunakan kapal laut, yaitu kapal Tarakan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Kuota yang diterima Indonesia saat itu sekitar 10.000 orang, dan peserta yang berangkat mencapai sekitar 9.907 jamaah. Pelepasan dilakukan oleh Menteri Agama, KH Abdul Wahid Hasyim, yang menyampaikan harapan agar pelayanan terhadap jamaah sesuai dengan kehormatan mereka.
Perjalanan haji umat Islam Indonesia pada era pra-kemerdekaan merupakan sebuah perjalanan spiritual yang juga sarat dengan makna historis, politik, dan kebangsaan. Dari pelayaran panjang yang penuh risiko dan intervensi kolonial, muncul semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur religius. Organisasi seperti Muhammadiyah mulai membangun strategi mandiri dalam pengelolaan haji. Selain itu, misi haji resmi pertama Republik Indonesia membawa cerita tentang diplomasi dan pengakuan internasional sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan.
Dengan memahami sejarah “Haji Pra Kemerdekaan,” kita tidak hanya mengapresiasi dimensi religius dari ibadah haji, tetapi juga melihat bahwa di balik ritualnya, terdapat kekuatan kolektif umat untuk mempertahankan martabat, kemerdekaan, dan identitas bangsa. Semoga pemahaman ini menjadi sumber inspirasi bagi generasi sekarang untuk meneguhkan hubungan antara spiritualitas dan perjuangan social, dan menjadikan prosesi ibadah haji hanya berhenti sebagai ibadah mahdah yang bersifat pribadi tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki efek bagi peradaban bangsa dan dunia.
H. Nasrudin, SPdI, SE, MSI, penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah dan Petugas Haji Daerah Purworejo tahun 2025